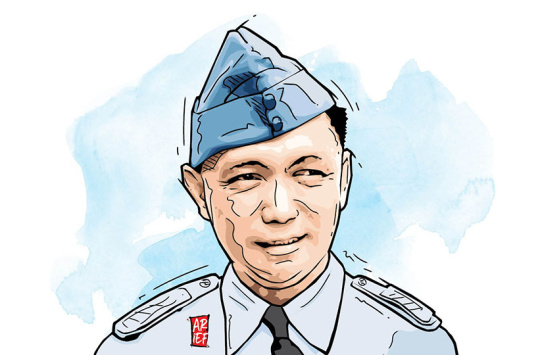Testimoni, Suara Sunyi yang Menanti Nurani
Menulis, bagi saya, bukan sekadar merangkai kata. Ia adalah laku batin, suatu tanggung jawab moral yang lahir dari kesadaran bahwa setiap kalimat yang dilemparkan ke ruang publik punya dampak.
Menulis bisa jadi cahaya yang menerangi, tetapi juga bisa jadi api yang membakar.
Itulah sebabnya, saya memilih untuk selalu berhati-hati. Bukan karena takut dikritik, melainkan karena sadar bahwa dalam zaman gaduh ini, kata-kata bisa jadi jembatan, atau justru jurang.
Ketika saya menulis tentang para aeronautika Indonesia yang kini tersebar di berbagai penjuru dunia, saya tak menyangka tulisan itu memantik percakapan.
Komentar-komentar pun mengalir, sebagian setuju, sebagian menggugat, dan sebagian—yang justru paling membekas—berisi pengakuan jujur dari mereka yang memilih tinggal di luar negeri dan tak ingin kembali.
Testimoni itu lebih dari sekadar respons; ia adalah jeritan lirih, suara jujur dari hati-hati yang terluka dan kecewa.
Secara filosofis, testimoni adalah bentuk kesaksian personal atas pengalaman. Dalam pemikiran Emmanuel Levinas, mendengar “yang lain” adalah tanggung jawab etis. Kita tak bisa mengklaim peduli pada bangsa ini jika menutup telinga dari suara anak-anaknya sendiri.
Suara mereka, yang lahir dari pengalaman langsung sebagai teknokrat, akademisi, atau peneliti di luar negeri, tak bisa dianggap sekadar keluhan. Ia adalah cermin bagi kegagalan kita dalam merawat harapan.
Sosiolog Anthony Giddens pernah menulis bahwa masyarakat modern dibentuk oleh reflexivity—kemampuan untuk merefleksikan dan mengubah struktur berdasarkan pengalaman.
Maka testimoni bukan sekadar curhat personal, melainkan kontribusi terhadap refleksi kolektif: mengapa anak-anak terbaik bangsa justru merasa asing di negerinya sendiri?
Sebagian dari mereka mengatakan bahwa mereka tidak ingin kembali bukan karena tak cinta tanah air, tapi karena tanah air tak memberi ruang bagi cinta itu tumbuh.
Mereka pernah mencoba berkontribusi, namun terhalang birokrasi yang kaku, politik yang gaduh, dan budaya kerja yang feodal.
Di tempat mereka kini berada, ide mereka dihargai, waktu mereka bernilai, dan kerja keras mereka membuahkan hasil—tanpa harus berurusan dengan gengsi, kolusi, atau senioritas tanpa kompetensi.
Seperti yang ditulis seorang diaspora dalam komentarnya, “Saya ingin pulang, tapi negeri ini belum siap untuk mendengar suara seperti saya.”
Dan memang, seberapa siap kita mendengar, bukan hanya memerintah? Bukankah ini soal martabat, bukan sekadar gaji atau fasilitas?
Mendengar dengan nurani, bukan telinga politik
Di tengah gegap gempita kampanye pembangunan dan jargon-jargon kemajuan, testimoni diaspora adalah jeda sunyi yang penting. Seperti yang dikemukakan Viktor Frankl dalam Man’s Search for Meaning, manusia tak sekadar mencari kenyamanan, tetapi makna.
Jika para profesional itu merasa tak lagi menemukan makna di tanah airnya, maka yang hilang bukan hanya mereka, tetapi juga ruh dari bangsa ini sendiri.
Apakah para pemangku negeri membaca tulisan-tulisan seperti ini? Saya tak tahu. Tapi saya percaya, di antara mereka masih ada yang memiliki kepekaan jiwa, masih ada yang mendengar bukan sekadar demi elektabilitas.
Kita tak bisa memaksa para profesional itu pulang, apalagi dengan dalih nasionalisme kosong. Tapi kita bisa bertanya: apakah negeri ini sudah menjadi rumah yang layak untuk mereka tempati kembali?
Rumah yang mendengar, menghargai, memberi ruang berkembang, dan melindungi martabat para pemilik ilmunya.
Mungkin testimoni-testimoni itu tampak kecil dan sunyi. Tapi dalam sunyi itulah gema perubahan bisa lahir. Testimoni mereka bukan untuk menyalahkan, tapi untuk menyadarkan.
Seperti suara hati yang lembut namun jujur, ia mungkin tak viral, tapi bisa mengetuk nurani—jika nurani itu belum sepenuhnya mati.
Saya tak ingin menyalahkan siapa pun. Saya hanya ingin mengajak merenung: kita semua—termasuk para pejabat negeri ini—sudahkah benar-benar mendengar testimoni anak-anak bangsa yang menjerit sunyi dari kejauhan?
Seperti yang dikatakan filsuf Alain de Botton, “Bangsa yang besar tak hanya ditentukan oleh kekuatan militernya, tetapi oleh seberapa baik ia memperlakukan para pemimpinnya masa depan—yang mungkin kini sedang menunggu untuk pulang, dalam diam.”
Dan kepada para pemangku negeri, mungkin ini saatnya mendengar. Bukan sekadar membaca.
| Editor | : | Editor Kontemporer |