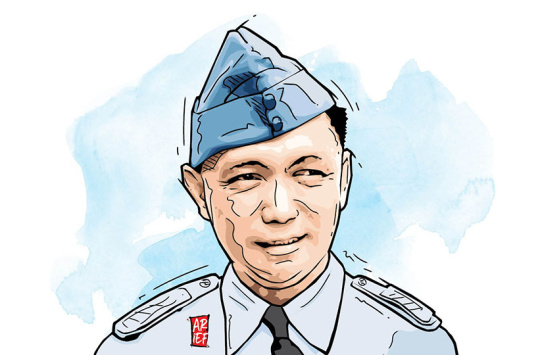Siskamling? Bayar Calo Sajalah!
ISTILAH yang tepat untuk melaksanakan sistem keamanan keliling (siskamling) atau melakukan ronda malam di lingkungan kita dalam bahasa Sunda adalah “ngaronda”.
Di desa di mana saya dibesarkan, setiap kepala keluarga di lingkungan kami pasti terkena ronda malam untuk menjaga keamanan lingkungan sekitar. Ada atau tidak ada maling, pokoknya keliling kampung untuk siskamling.
Bahkan tidak sedikit cerita dari para orangtua dan tetangga dulu, alih-alih meronda yang dipergoki bukan maling tetapi sejenis makhluk halus. Begitulah.
Tulisan ini tentu saja bukan membahas makhluk halus dan semacamnya. Saya sekadar mengenang masa lalu saja di mana orang-orang sedemikian peduli terhadap lingkungannya.
Menunjukkan kepedulian yang tinggi untuk hidup saling menjaga. Seakan-akan tertimpa aib dan dosa besar kalau tidak ikut “ngaronda”. Seakan-akan asosial jika tidak ikut serta menjaga lingkungannya.
Menjaga lingkungan secara bersama-sama dari kemungkinan ancaman dan gangguan maling. Saya masih ingat suara “kohkol”, yaitu buluh bambu yang dilubangi memanjang bagian tengahnya untuk menampung suara ketika badan bambu itu dipukul.
Suaranya bersahut-sahutan. Khas dan asyik sekali, bagai musik pengiring tidur saja layaknya.
Ada kode yang harus dihapal dan dipahami. Jika suara yang dipukul dua atau tiga kali dengan tempo lambat, itu berarti keadaan aman dan orang boleh tidur nyenyak di balik selimut.
Tetapi bila “kohkol” dipukul secara sporadis dengan tempo cepat, berarti maling sedang beraksi dan warga masyarakat diharapkan terbangun demi mendengar kegaduhan itu.
Pukulan yang bertalu-talu juga untuk menyatukan kembali para peronda dalam satu titik, biasanya di pos ronda, agar bisa bersama-sama bertindak. Semacam komandolah.
Anehnya, informasi mengenai tanda-tanda bunyi “kohkol” itu juga ditempel di pos ronda. Artinya, si maling bisa saja menghapal tanda bunyi itu untuk antisipasi lari atau sembunyi.
Begitu seterusnya. Setiap malam ada ronda malam. Belakangan “kohkol” jarang digunakan lagi. Peronda cukup memukul-mukul tiang listrik saja. Ibarat music, nadanya sudah sumbang dan tidak enak didenagr lagi. Mengapa juga tiang listrik dijadikan korban pemukulan.
Suaranya yang cempreng sungguh merusak telinga warga. Bahkan di beberapa kampong, untuk bisa saling berkomunikasi di antara peronda, mereka biasa menggunakan radio komunikas.
“Break, break… ada yang mencirigakan di belakang rumah Pak Haji!” Lalu dijawab, “Dikopi, siap meluncur.
Ganti!” Itu percakapan di antara para peronda selepas “kohkol” dan tiang listrik sekarat, yakni lewat alat canggih bernama radio komunikasi. Sekarang, komunikasi antarperonda tentu dilakukan melalui telepon seluler atau bahkan ponsel pintar.
Di lingkungan sekarang dimana saya tinggal, di sebuah perumahan di pinggiran Bintaro, “ngaronda” sudah tidak dilakukan lagi oleh para warga. Para peronda digantikan oleh Satpam yang digaji warga lewat iuran bulanan.
Tidak ada suara “kohkol” lagi karena di pendopo atau gardu memang tidak ada alat bunyi perkusi tradisional itu. Barangkali kalau pun ada, malah bisa dijadikan barang mainan anak-anak yang memukul “kohkol” itu di sembarang waktu sesuka mereka.
Akan tetapi, ronda malam sesekali diberlakukan lagi bagi warga kompleks jika “keadaan genting” terjadi lagi.
Yang dimaksud “keadaan genting” itu jika pencurian di kompleks datang secara berturutan atau itu tadi, adanya ancaman perusuh yang akan menjarah properti milik warga perumahan. Dan yang dicuri bukan hanya sepeda motor, tetapi mobil.
Suasana ronda malam terasa sekali waktu terjadi kerusuhan Mei 1998 lalu, di mana “ngaronda” wajib dilakukan setiap malam oleh warga pria.
Wah, mengapa juga ya ronda malam itu hanya diberlakukan pada saat terjadi kerusuhan atau keadaan genting saja. Bukankah lebih baik “ngaronda” jalan terus meski suasana sedang aman sekalipun?
Kalau sikap ini menjalar pada para penjaga negeri ini baik yang bertugas di laut, di udara dan di darat, bisa jebol Ibu Pertiwi ini. Bukan tidak mungkin banyak pulau-pulau terluar mengalami nasib seperti Sipadan-Ligitan.
Bisa-bisa Pulau Miangas yang berbatasan dengan Filipina diklaim sebagai pulau milik Filipina.
Jadi, jangan sampailah semangat “ngaronda” hanya dalam keadaan genting itu menerpa para penjaga kedaulatan wilayah NKRI. Genting tidak genting ya harus patrol, harus “ngaronda” dalam skala nasional.
Di beberapa tempat, di sejumlah kompleks, dan bahkan pada masyarakat pinggiran kota, sudah umum terjadi kalau “ngaronda” menjaga keliling kerap di-out sourcing-kan kepada orang lain.
Ada warga yang bersedia menjadi “calo”, biasanya warga dari luar kompleks yang sudah dikenal warga kompleks, asalkan tentu saja dengan imbalan.
Demikian juga kalau ada kerja bakti membersihkan lingkungan, juga bisa menyuruh orang lain yang mewakili orang yang seharusnya “ngaronda” atau kerja bakti.
Bisa sopir pribadi, bisa pembantu pria di rumah kita. Tentu saja orang itu kita bayar. Di satu sisi, cara ini memang membuka peluang kerja bagi mereka yang menghendaki pekerjaan itu.
Lumayan ‘kan konversi sekali “ngaronda” atau kerja bakti itu bisa Rp 50.000 sampai Rp 150.000.
Saya tidak tahu, apakah pendidikan moral Pancasila atau pendidikan wawasan kebangsaan modern yang sudah tidak saya ikuti lagi itu membuka peluang untuk meng-out sourcing-kan sebuah upaya mengguyubkan lingkungan terkecil di masyarakat dalam bentuk “ngaronda” atau kerja bakti ini.
Adakah buku kebangsaan atau wawasan kebangsaan yang menjelaskan bahwa pertemuan dalam sebuah forum “ngaronda” mengajarkan warga untuk saling mengenal satu sama lainnya, untuk bisa bergotong royong jika ada sesuatu yang perlu diselesaikan bersama?
Bukankah “ngaronda” juga momen yang baik untuk saling merasakan bahwa mereka adalah satu bangsa, Indonesia, yang hidup damai dan berdampingan? Dalam konteks agama yang saya anut, bukankah “ngaronda” itu bentuk lain dari silaturahmi?
Atau semuanya selesai dengan solusi instan, tidak harus susah-susah, capek-capek, dan dingin-dingin kalau “ngaronda” bisa dialihdayakan.
Bayar sajalah, toh ada calo yang siap menggantikan tugas kita asalkan sudah sepengetahuan Ketua RT.
Sebagai warga kompleks perumahan di mana saya mukim, jelek-jelek begini saya tidak pernah membayar “calo ronda” loh. Bukan sok gaya, saya tetap Siskamling kalau sudah kena gilirannya.
Siskamling, ketika ronda malam diganti uang kerahiman
Di masa kecil saya di sebuah desa di Tatar Sunda, ada satu kegiatan yang terasa lebih dari sekadar kewajiban. Ngaronda, namanya Istilah Sunda untuk ronda malam ini dulu menjadi semacam “ritual” kebersamaan.
Tiap kepala keluarga pasti akan kena giliran. Bukan karena perintah aparat, melainkan karena kesadaran, bahwa “kalau bukan kita yang jaga lingkungan, siapa lagi?”
Malam-malam gelap jadi akrab dengan suara bambu dipukul, biasa disebut kohkol. Ada yang memukul dua kali perlahan—tanda aman, boleh lanjut tidur. Tapi kalau suara bertalu-talu dan tergesa, itu pertanda maling berkeliaran.
Semua warga paham. Semua siap siaga. Bahkan, maling pun mungkin tahu “kode bunyi” itu. Tetapi yang terpenting rasa aman dibangun bersama.
Namun, waktu berubah. Peradaban kota melaju, kompleks perumahan menjamur, dan... suara kohkol pun menghilang. Digantikan suara lain, “Pak, ronda giliran saya diganti, ya. Nanti saya bayar yang ngerondanya.”
Dari “Kohkol” ke transfer, evolusi jaga malam
Pada banyak kawasan urban hari ini, termasuk perumahan elite pinggiran Jakarta, ronda malam alias Siskamling masih ada, tetapi itu secara administratif. Fungsinya lebih mirip daftar giliran setoran.
Petugas keamanan diserahkan ke satpam profesional, dibayar iuran bulanan. Kalau pun warga kena giliran, ya tinggal bayar Rp100.000–Rp150.000 ke "pengganti".
Tak bisa ronda? Gampang, tinggal alih daya. Seorang sopir, asisten rumah tangga pria, bahkan tetangga dari kampung sebelah bisa dibayar untuk menggantikan giliran. Praktis? Iya. Efektif membangun keakraban? Tentu tidak.
Padahal, jika mau jujur, Siskamling bukan sekadar menjaga maling. Ia adalah pembentuk modal sosial, tempat kita belajar menyapa tetangga yang jarang ditemui, bertukar cerita, bahkan kadang curhat tentang harga cabai atau anak yang susah bangun subuh.
Dalam sosiologi, modal sosial merujuk pada jaringan, norma, dan kepercayaan yang memungkinkan masyarakat bekerja sama secara efektif. Robert Putnam, dalam bukunya Bowling Alone (2000), mencatat bahwa semakin modern masyarakat, semakin individu merasa bisa hidup "sendirian".
Akibatnya, partisipasi dalam kegiatan Bersama seperti ngaronda tergerus oleh kepraktisan dan privatisasi.
Indonesia pun tidak kebal dari gejala ini. Data dari BPS (2023) menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan turun dari 57,1% pada 2010 menjadi 41,6% pada 2022.
Salah satu sebabnya adalah meningkatnya gaya hidup individualistis, khususnya di wilayah perkotaan.
Bila dulu ronda malam jadi ruang silaturahmi, sekarang cukup satu klik di WhatsApp grup RT: “Saya bayar calonya ya, Pak.” Semangat kebersamaan tergantikan oleh efisiensi transaksional.
Apa yang hilang?
Ketika ronda dikerjakan oleh "outsourcing", kita kehilangan lebih dari sekadar jam jaga malam. Kita kehilangan, pertama, rasa memiliki lingkungan: Jika rumah tetangga kemalingan, kita merasa "itu urusannya".
Kedua, solidaritas sosial di mana tidak ada lagi obrolan di pos ronda tentang harga beras, tim bola, atau kabar tetangga sakit.
Ketiga, kesadaran keamanan kolektif di saat kita menjadi penonton, bukan bagian dari sistem pertahanan warga.
Pernahkah kita bertanya, mengapa saat kerusuhan besar seperti Mei 1998 dulu, ronda kembali dilakukan? Karena dalam krisis, insting kolektif itu muncul kembali. Sayangnya, begitu krisis lewat, ronda kembali dipasrahkan ke petugas bayaran.
Fenomena ini tak hanya soal kompleks perumahan. Ini miniatur dari cara kita melihat negara. Jika keamanan lingkungan saja bisa dibayar calo, apakah pertahanan negara pun akan kita serahkan sepenuhnya ke “yang profesional saja”?
Bayangkan jika para penjaga kedaulatan—TNI, Satpol, penjaga laut di perbatasan—berpikir seperti kita: "Ah, tidak genting, ngapain ronda."
Maka tidak mustahil, pulau-pulau terluar seperti Miangas, Rondo, atau Natuna bisa hilang seperti Sipadan dan Ligitan yang dulu kita relakan ke Malaysia karena tak terjaga optimal.
Negara tak selalu roboh karena perang. Kadang, ia lapuk pelan-pelan karena warganya enggan dan tidak peduli.
Partisipasi demokratis
Dalam konteks kebangsaan, Siskamling adalah latihan miniatur bagi partisipasi demokratis. Kita hadir, kita berjaga, kita gotong royong. Dan yang paling penting, kita belajar bahwa keamanan bukan hanya tanggung jawab "orang lain", tapi kita semua.
Dalam ajaran agama pun, silaturahmi dan menjaga tetangga adalah bagian dari iman. Maka, ronda bisa menjadi ibadah sosial. Nilainya bukan pada berapa kilometer yang dijalani malam itu, tapi pada kesediaan hadir untuk yang lain.
Tentu tidak salah jika kadang kita perlu bantuan orang lain untuk menggantikan giliran ronda. Kita pun tidak selalu bebas waktu.
Tetapi jangan jadikan itu sebagai kebiasaan permanen. Jangan sampai kita hidup di kompleks elit tetapi tak mengenal siapa tetangga kiri-kanan.
Pertanyaannya bukan soal “mampu bayar atau tidak”, tetapi “mau hadir atau tidak.”
Dan, ya, saya tetap ikut giliran ronda. Jelek-jelek begini, saya masih percaya bahwa ronda malam lebih dari sekadar jalan-jalan larut malam. Ia adalah pertahanan moral paling awal untuk menjaga rumah, lingkungan, dan bahkan negara.
Kalau kamu?
| Editor | : | Editor Kontemporer |