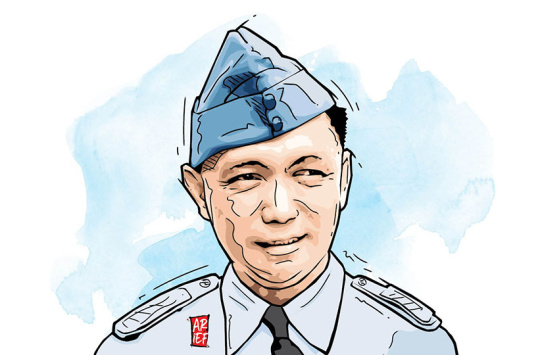Cerita yang Tidak Tertulis di Kota
Malam pertama di trotoar Sudirman lampu jalan mulai menyala dan sebagian besar pekerja kantoran pulang. Tapi bagi Tia, penjual bakpia di Sudirman, justru rutinitasnya baru dimulai. Trotoar yang sepi adalah mata pencariannya, tempat membuka meja, menyalakan lampu, dan menunggu malam tiba.
Kebanyakan orang melihat kerlip gedung tinggi, truk barang, atau bus transjakarta. Tapi ada kehidupan lain yang jarang terekspos, para pekerja informal yang berada di pinggir, bukan karena mereka ada di pinggiran tapi karena kota tumbuh tanpa menjadikan mereka bagian pusatnya.
Data substansial, realita tak tersorot
Menurut Badan Pusat Statistik, pada Februari 2025, jumlah pekerja informal telah mencapai 59,40% dari total populasi angkatan kerja atau sekitar 86,58 juta orang dari 145,77 juta pekerja di seluruh Indonesia.
Mayoritas mereka ditemukan di kota-kota besar: Jakarta, Bandung, Surabaya. Keadaan ini bukan sekadar statistik, melainkan representasi bahwa banyak warga telah beradaptasi pada fleksibilitas, bukan keamanan pekerjaan.
Tingkat pengangguran yang mencapai 7,28 juta orang semakin menegaskan bahwa informalitas bukan pilihan gaya hidup, tetapi sarana bertahan hidup saat peluang formal tidak memadai.
Ekosistem ekonomi alternatif, tapi rentan
Digambarkan dalam studi tentang pedagang kaki lima (PKL) di Jakarta dan Depok. Mereka membangun “ekonomi ciptaan sendiri”, sistem kekeluargaan, saling memberi info lincah via WhatsApp, hingga memanfaatkan warung kopi pinggir trotoar sebagai co-working space informal.
Namun, rezim kota sering memberi tekanan. Proyek pelebaran trotoar membuat jarak antar gerobak dan pembeli melebar, pembaruan rambu membuat lokasi strategis berpindah, atau regulasi parkir anyar yang menggerus alur pelanggan.
Bagi mereka, sekadar perubahan rute keliling saja bisa membuat penghasilan harian anjlok.
Di balik angka, ada kehidupan yang langsung terpengaruh
Bukan hanya angka. Ada cerita manusia di baliknya. Suryadi yang hafal senyum pelanggannya, Tia yang selalu menyiapkan bakpia rasa lokal tanpa resiko profesi formal, tapi selalu peduli rasa hingga tukang parkir yang menjadi pusat info razia, lokasi baru, hingga omset harian pekerja informal.
Dalam wacana mainstream, mereka sering disamakan dengan beban ekonomi, padahal mereka adalah denyut nadi yang menjaga agar kota tetap memiliki warna kehidupan. Tanpa mereka, kota hanyalah kerumunan rutinitas tanpa jiwa.
Ketika kota tumbuh dengan peta formal, ada anak-anaknya yang tersingkir bukan karena tidak produktif, tapi karena tidak punya tempat di tata kota resmi. Pekerja informal bukan “penghindar pajak”, melainkan pelaku ekonomi tangguh yang perlu dilindungi.
Mereka pantas masuk dalam perencanaan kota, bukan hanya dianggap variabel yang “tumbuh nyaman di celah”. Karena saat kota ingin hidup penuh, meja-mereka juga layak mendapat space dan pengakuan.
| Editor | : | Editor Kontemporer |