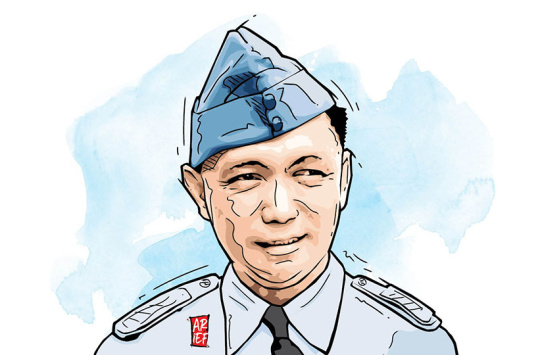Kembalikan Ajaran Budi Pekerti Padaku!
Tahun 2004. Sebuah tempat di Indonesia yang kala itu tengah membara oleh konflik. Saya menyaksikan seorang anak muda dikeroyok hingga tubuhnya dibakar hidup-hidup oleh massa yang kalap.
Ia berteriak, “Ampun… tolong…,” tetapi jeritannya tak mampu menembus tembok kemarahan yang telah kehilangan nurani.
Bahkan hingga dua dekade berlalu, gema jeritan itu masih kerap datang menghampiri kesadaran saya—bukan hanya sebagai jurnalis, tapi sebagai manusia.
Pertanyaan yang mengganggu saya sejak saat itu adalah: ke mana perginya ajaran budi pekerti kita?
Emile Durkheim, sosiolog besar Perancis, pernah mengatakan bahwa masyarakat dapat mengalami “anomie”, suatu kondisi di mana masyarakat kehilangan norma ketika tatanan sosial goyah dan nilai-nilai kolektif tidak lagi dihormati.
Ketika norma-norma moral tidak ditanamkan sejak dini, atau lebih parah lagi: dicabut secara sistematis dari sistem pendidikan, kekerasan menjadi hal yang mudah dijustifikasi, bahkan dilakukan bersama-sama.
Psikolog sosial Philip Zimbardo melalui eksperimentalnya di Stanford Prison Study menunjukkan bahwa manusia biasa bisa menjadi monster dalam kondisi tertentu, jika norma-norma etis tak lagi membimbing tindakan.
Massa yang saya lihat hari itu bukanlah iblis—mereka adalah manusia biasa yang telah kehilangan kompas moralnya.
Budi pekerti bukan sekadar pelajaran formal yang diajarkan di sekolah. Ia adalah bagian dari sistem nilai, dari kebudayaan kita, dari inti kemanusiaan itu sendiri. Ajaran ini mengandung sikap menghargai orang lain, hidup dalam kerukunan, tolong-menolong tanpa pamrih, jujur, rendah hati, dan bertanggung jawab.
Namun kini, nilai-nilai itu terasa menguap dari ruang publik. Dalam laporan Komnas HAM (2023), Indonesia mencatat 1.212 kasus kekerasan kolektif yang mencakup konflik horizontal, penganiayaan, dan persekusi.
Di sekolah, data Kemendikbudristek menunjukkan peningkatan signifikan perundungan dan kekerasan antar siswa pasca pandemi.
Pertanyaannya: adakah ruang dalam pendidikan kita hari ini yang benar-benar menanamkan nilai-nilai luhur ini, bukan sekadar menyodorkan hafalan Pancasila?
Diajarkan lewat Tindakan
Saya masih ingat, pelajaran budi pekerti di SD saya dulu bukan hanya tentang teori. Ia hidup dalam praktik sehari-hari: bagaimana mengucapkan salam, membantu teman yang jatuh, memberi tempat duduk pada yang lebih tua, atau mengantarkan makanan untuk tetangga sakit. Guru kami tidak hanya mengajarkan, mereka menjadi teladan.
Hari ini, dalam masyarakat yang diburu performa dan pencapaian akademik, pelajaran moral sering hanya menjadi sisipan di lembar RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran).
Padahal seperti dikatakan Prof. Komaruddin Hidayat, “Karakter tidak bisa diajarkan, tetapi ditularkan.” Jika guru dan orang tua tidak lagi hidup dalam nilai-nilai budi pekerti, bagaimana mungkin anak-anak akan mempraktikkannya?
Dalam dunia yang penuh polarisasi, hoaks, kebencian berbasis identitas, dan kekerasan simbolik, budi pekerti menjadi vaksin sosial. Ia bukan nostalgia masa lalu, melainkan kebutuhan peradaban masa kini.
Dalam riset yang dilakukan oleh World Economic Forum (2024), soft skills seperti empati, etika kerja, kerja sama, dan kemampuan menyelesaikan konflik akan menjadi keterampilan inti masa depan. Namun ironis, nilai-nilai itu justru tidak diperkuat secara sistemik dalam pendidikan kita.
Belajar matematika dan sains itu penting. Tapi jika anak-anak kita tidak tahu bagaimana menghormati perbedaan, mengelola konflik, atau menyapa dengan sopan, maka pendidikan itu kehilangan jiwanya.
Saya pernah bertanya kepada sekelompok siswa SMA dalam sesi literasi karakter: “Apa yang paling kalian inginkan diajarkan di sekolah?” Salah satu dari mereka menjawab, “Bagaimana caranya hidup sebagai manusia yang baik.”
Jawaban sederhana, tapi menyentuh. Karena rupanya, di tengah gempuran teknologi, mereka justru merasa hampa nilai.
Kita juga menyaksikan kampanye sosial seperti #GerakanSekolahMenyenangkan atau “Character Day” yang mulai digiatkan di beberapa sekolah swasta dan komunitas belajar di Indonesia.
Mereka mencoba menanamkan kembali pelajaran etika, empati, dan tanggung jawab sebagai bagian dari keseharian, bukan hanya teori.
Budi pekerti dan bangsa yang sakit jiwa
Ketika seorang politisi korupsi triliunan, lalu tampil seolah-olah pahlawan di depan kamera, itu bukan sekadar masalah hukum. Itu masalah budi pekerti yang tak ditanamkan. Ketika ada sekelompok orang merasa berhak membakar rumah ibadah orang lain, itu bukan cuma ekstremisme. Itu kegagalan sistem nilai.
Sebagaimana kata Erich Fromm dalam The Sane Society, masyarakat bisa menjadi “sakit jiwa” bila kehilangan cinta, empati, dan rasa tanggung jawab terhadap sesama. Dan budi pekerti adalah akar dari ketiga hal itu.
Kembalikan ajaran budi pekerti pada anak-anak kita. Bukan dalam bentuk dogma moralitas sempit, tapi dalam bentuk nilai-nilai hidup yang diteladani. Bukan sekadar pelajaran, tapi praktik keseharian.
Mulailah dari rumah, dari sekolah, dari ruang publik. Dari cara kita berbicara di media sosial, dari bagaimana kita menanggapi perbedaan, dari bagaimana kita memperlakukan mereka yang lebih lemah.
Seperti kata Mahatma Gandhi, “You must be the change you wish to see in the world.” Dan perubahan itu dimulai dari budi pekerti—sekecil apa pun.
| Editor | : | Editor Kontemporer |